https://id.trip.com/moments/destination-huixian-2313/
2025 Huixian Travel Guide: Must-see attractions, popular food, hotels, transportation routes (updated in Desember)
Huixian Cuaca hari ini
Cerah 1-15℃

Trending di Huixian
Semua Momen Trip tentang Huixian
Gambaran Singkat Rute Pendakian Inti Dua Hari di Nan Taihang
Nan Taihang, sebuah galeri pemandangan pegunungan yang menggabungkan keagungan, bahaya, keunikan, dan keindahan, memang merupakan rute pendakian yang sangat klasik. Rencana perjalanan dua hari yang kamu buat sangat ringkas dan bisa memberikan pengalaman inti yang baik. Saya telah menyusun panduan pendakian praktis untukmu, semoga membantu perjalananmu berjalan lancar. Tabel rute di bawah ini secara langsung menampilkan perencanaan rute inti, sorotan, serta informasi penting tentang transportasi dan tiket, kamu bisa memahaminya dengan cepat. Rencana Perjalanan: Hari Pertama: Bali Gou Hari Kedua: Wanxian Shan & Tianjie Shan Pengalaman Inti: Menikmati "Dunia Air Utara", menyaksikan pemandangan megah Air Terjun Tianhe. Mendaki Jalan Gantung Guoliang, naik Tianjie Shan untuk melihat pemandangan awan di ngarai. Kegiatan Utama: - Menjelajahi kawasan Taohuawan dan Kuil Dewa Gunung. - Sampai di Air Terjun Tianhe, bisa melewati Gua Tirai Air. - Pagi: Mendaki koridor tebing curam (Jalan Gantung Guoliang), berfoto di balkon pemandangan di rumah tebing. - Sore: Menuju Huilong Tianjie Shan, menjelajahi Galeri Puncak Awan. Transportasi dan Tiket: - Referensi tiket: 62 yuan (harus membeli tiket bus wisata tambahan 30 yuan). - Transportasi internal: disarankan naik bus wisata ke atas gunung (10 yuan/orang), turun gunung dengan berjalan kaki sambil menikmati pemandangan. - Tiket Wanxian Shan: 107 yuan (termasuk bus wisata). - Tianjie Shan: termasuk dalam tiket gabungan kawasan Bali Gou, sudah termasuk bus wisata. 🥾 Rincian Perjalanan Harian dan Tips Ramah Berdasarkan tabel di atas, berikut beberapa saran dan hal yang perlu diperhatikan agar perjalananmu lebih lancar. 🌊 Hari Pertama: Bali Gou · Inti Alam Pegunungan dan Air · Pagi: Setelah masuk kawasan, kamu bisa naik bus wisata sebentar untuk menghemat tenaga, lalu mulai menjelajah dari Taohuawan. Di sini air kolam sangat jernih, ada aktivitas air seperti rakit bambu, kamu bisa bersantai bermain air. · Siang: Menuju ke titik utama Air Terjun Tianhe. Air terjun ini adalah ikon Bali Gou. Di belakang air terjun ada Gua Tirai Air, pengalaman unik melewati air terjun ini, kabut air menyapu wajah sangat menyegarkan. Jika hujan reda dan cerah, kamu juga bisa melihat pelangi di samping air terjun. · Sore: Setelah menikmati air terjun, kamu bisa memilih menantang tangga 888 anak tangga atau turun gunung dengan santai sambil menikmati pemandangan Sungai Batu Merah dan Kolam Giok. ⛰️ Hari Kedua: Wanxian Shan & Tianjie Shan · Keberanian Tebing Curam · Pagi: Langsung menuju Desa Guoliang di kawasan Wanxian Shan. Pengalaman inti adalah mendaki koridor tebing curam (Jalan Gantung Guoliang). Terowongan yang dipahat di tebing batu merah ini sendiri adalah sebuah epik yang mengagumkan. Jangan lupa berhenti di balkon pemandangan di rumah tebing, ini adalah spot terbaik untuk memotret panorama jalan gantung. · Siang: Kamu bisa mencicipi masakan rumah di Desa Guoliang, tumis daun bawang gunung dengan telur ayam kampung dan agar-agar biji ek adalah cita rasa khas lokal, biaya sekitar 40 yuan per orang. · Sore: Menuju Huilong Tianjie Shan. Galeri Puncak Awan di sini adalah jalan gantung di udara, bisa melihat ngarai Taihang 360°, merupakan balkon pemandangan terbaik untuk menikmati tebing batu merah dan lautan awan ngarai. Jika hujan reda dan cerah, kemungkinan besar pagi berikutnya kamu akan melihat lautan awan. 💰 Referensi Anggaran dan Akomodasi · Tiket dan Transportasi: Total biaya tiket utama dan bus wisata dua hari sekitar 199 yuan/orang (Bali Gou 62+30, Wanxian Shan 107). Tianjie Shan biasanya sudah termasuk dalam tiket gabungan kawasan Bali Gou. · Pilihan Akomodasi: Disarankan menginap malam pertama di sekitar kawasan Bali Gou atau Kota Huixian. Di sekitar Bali Gou banyak penginapan seperti Binhe Shengju, Qian Na Meisu, memudahkan perjalanan hari berikutnya. Jika ingin pengalaman unik, malam kedua bisa memilih kamar balkon tebing di Desa Guoliang, harga sekitar 200 yuan/malam, membuka jendela langsung pemandangan pegunungan Taihang. · Kuliner: Selain masakan rumah yang disebutkan, setelah kembali ke pusat Kota Xinxiang, jangan lewatkan hidangan khas lokal—Gao Ji Daging Kambing Rebus Merah, makan dengan kuah daging kambing dan mie tipis adalah cara makan tersembunyi penduduk lokal, biaya sekitar 60 yuan per orang. 📌 Persiapan Sebelum Berangkat dan Tips Praktis 1. Musim Terbaik: April hingga Oktober adalah waktu terbaik untuk menjelajahi Nan Taihang. Juli-Agustus air terjun paling deras, pengalaman bermain air terbaik; musim gugur dengan langit cerah dan udara segar adalah waktu emas untuk melihat lautan awan dan pendakian. 2. Perlengkapan Wajib: · Sepatu gunung anti selip: ini sangat penting! Batu di ngarai licin, beberapa jalan gantung juga butuh daya cengkeram yang baik. · Suhu di pegunungan berubah drastis, bawa jaket tipis. · Perlengkapan pelindung matahari: tabir surya, topi pelindung. · Air minum cukup dan camilan berenergi. 3. Peringatan Hindari Kesalahan: · Harus beli tiket bus wisata: jarak antar titik di kawasan sangat jauh, tidak realistis berjalan kaki, membeli tiket bus wisata wajib. · Utamakan keselamatan: jangan naik motor pribadi, sangat berbahaya. Saat berfoto di balkon pemandangan, perhatikan kaki, jangan terlalu dekat pagar pengaman. 4. Kejutan Tersembunyi: Jika menginap di Wanxian Shan, jangan lupa lihat bintang di malam hari. Polusi cahaya sangat sedikit, tempat ini sangat cocok untuk mengamati bintang. 💎 Ringkasan Rute Rute dua hari ini secara tepat menangkap dua daya tarik utama Nan Taihang: keindahan alam Bali Gou dan tebing curam megah Wanxian Shan serta Tianjie Shan. Perencanaan dan persiapan yang baik memungkinkan kamu merasakan semangat megah "Punggung Dunia Taihang" dalam waktu terbatas. Semoga panduan ini membantu kamu mewujudkan perjalanan Nan Taihang yang sempurna. Jika kamu memiliki permintaan khusus terkait kuliner atau akomodasi di sepanjang perjalanan, misalnya ingin memesan penginapan tertentu, saya bisa membantu mencari informasi lebih detail lagi.Ward Melissa Missy5Panduan Wisata 2 Hari di Xinxiang
Eksplorasi Penuh Alam Nan Taihang dan Kuliner Utara Henan 📅 Hari 1: Gunung Wanxian · Keajaiban Jalan Gantung 🚗 Rekomendasi Transportasi Mengemudi sendiri dari Zhengzhou selama 1,5 jam (langsung navigasi ke "Area Wisata Gunung Wanxian") Setelah tiba di Stasiun Xinxiang Timur dengan kereta cepat, sewa mobil atau ikut carpool (sekitar 80 yuan/orang) ⛰️ Pagi: Jalan Gantung Guoliang 🎫 Tiket: 107 yuan (termasuk transportasi di area wisata) ⏰ Waktu yang disarankan: 3 jam ✨ Wajib Dicoba: Jalan kaki 1,2 km di koridor tebing (lokasi syuting film "Raise Your Hands") Platform pemandangan di rumah tebing untuk foto panorama Tantangan teriakan air mancur untuk menguji kapasitas paru-paru 🍜 Makan Siang: Masakan Rumah Pegunungan 📍 Rekomendasi: Rumah Makan Wangmangling di Desa Guoliang 🍲 Menu wajib: Telur ayam kampung tumis daun bawang gunung, agar-agar kacang ek (sekitar 40 yuan per orang) 💦 Sore: Lembah Danfen Nanping 🚌 Naik bus wisata ke Nanping (20 menit) 🏞️ Aktivitas: Mendaki air terjun kelompok Heilongtan Keajaiban geologi Batu Matahari Bulan Bintang Trekking di hutan Gunung Wufeng (siapkan sepatu olahraga) 🏡 Rekomendasi Penginapan • Penginapan Desa Guoliang (kamar pemandangan tebing sekitar 200 yuan/malam) • Hotel Gunung Wanxian (standar bintang tiga sekitar 300 yuan/malam) 📅 Hari 2: Lembah Bali · Dunia Air Utara 🌅 Pagi Buta: Matahari Terbit di Tebing ⏰ 5:30-6:30 Sarapan di rooftop penginapan sambil menikmati matahari terbit dan lautan awan 📸 Spot foto: Situs Tangga Langit 🚣 Pagi: Air Terjun Tianhe 🎫 Tiket: 62 yuan (harus beli tambahan 30 yuan untuk bus wisata) ⏰ Aktivitas utama: Naik rakit bambu menembus celah sempit (20 yuan/orang) Bermain air di Kolam Giok Sungai Batu Merah Mendaki 888 anak tangga Tangga Langit (sesuaikan kemampuan) 🐑 Makan Siang: Kuliner Terbaik Xinxiang 🚗 Berkendara 1 jam kembali ke pusat kota 📍 Rekomendasi: Daging Kambing Rebus Merah Ge Ji (sekitar 60 yuan per orang) 🍖 Cara makan tersembunyi: Sup daging kambing dengan irisan roti 🏯 Sore: Makam Raja Lu atau Kuil Bigan (pilih salah satu) 1️⃣ Makam Raja Lu (tiket 50 yuan): Makam bawah tanah pangeran Dinasti Ming + Batu nisan terbesar tanpa tulisan 2️⃣ Kuil Bigan (tiket 40 yuan): Tempat asal-usul keluarga Lin di seluruh negeri 🚗 Tips Pulang Berangkat sebelum jam 16:00 untuk menghindari kemacetan sore di Zhengzhou 💰 Perkiraan Biaya (2 orang) Item Biaya Transportasi 400 yuan (sewa mobil/carpool + bahan bakar) Tiket Masuk 338 yuan (Gunung Wanxian + Lembah Bali) Penginapan 300 yuan (penginapan khas) Makan 300 yuan (termasuk hidangan daging kambing rebus merah) Lainnya 200 yuan (aktivitas + camilan) Total Sekitar 1500 yuan 📌 Saran dari Penduduk Lokal Waktu terbaik: April-Oktober, Juli-Agustus debit air terjun paling besar Panduan pakaian: Sepatu anti selip wajib (batu di lembah licin) Bawa jaket tipis karena perbedaan suhu besar Peringatan: Harus beli tiket bus wisata di area (jarak jalan kaki sangat jauh) Hati-hati naik motor pribadi (tidak aman) Rahasia tersembunyi: Nikmati bintang malam di Gunung Wanxian (polusi cahaya rendah) Coba jus hawthorn liar Taihang (5 yuan/botol) Bawa panduan ini dan berangkatlah, temukan sisi berbeda dari Nan Taihang! 🏔️sarapluto4Tur balik Hari Nasional sukses! 5 hari 4 malam di tempat rahasia musim gugur yang bahkan lebih liar dari Zhangjiajie
Liburan Hari Nasional ini sangat merekomendasikan permata tersembunyi ini—Ngarai Chijin setinggi 800 li! Saksikan tebing-tebing menjulang tinggi bermandikan sinar matahari musim gugur, dengan warna oker yang semarak. 🏜️ Jalan tebing tetap berbahaya seperti sebelumnya, kini memamerkan hamparan daun maple yang memukau, sebuah pemandangan yang juga dinikmati oleh kera-kera Gunung Ti'nao. 🐒 Telusuri lipatan-lipatan murni yang telah disertifikasi National Geographic, di mana ngarai berbentuk hati ini berbingkai emas. Jauh di dalam jalur setapak yang liar, cabang-cabangnya melengkung dengan buah hawthorn dan kesemek. 🌰 Habiskan 5 hari 4 malam menjelajahi negeri ajaib musim gugur yang tersembunyi, bahkan lebih liar daripada Zhangjiajie. Tidak ada jalan papan buatan manusia di sini, hanya romansa alam yang tak terjamah! Seberapa menakjubkankah ini? Anda harus melihatnya sendiri! Cara ke sana: ✈️ Tiba: Bandara Internasional Zhengzhou Xinzheng, naik bus bandara/kereta bawah tanah langsung ke pusat kota (sekitar 40 menit). 🚄 Kereta cepat: Stasiun Zhengzhou Timur, dengan koneksi langsung ke Shanghai, Guangzhou, Shenzhen, dan Beijing hanya dalam 3 jam! Informasi Penting Itinerary (termasuk makanan dan tempat check-in) ✅ Hari ke-1: Bertemu di Zhengzhou Akomodasi di hotel kota dengan transportasi yang nyaman, dan cicipi kuliner Henan! Objek Wisata: Museum Provinsi Henan, Kawasan Pemandangan Sungai Kuning, Kuil Shaolin Makanan: Mie Kuah, Ayam Panggang Daokou, Hu La Tang 🍜 ✅ Hari ke-2: Desa Guoliang - Tangga Langit - Menara Pengawas Berkendara ke Kawasan Pemandangan Gunung Wanxian, lalu daki Jalan Tebing Guoliang dan taklukkan jalur papan tebing! Nikmati pemandangan Tebing Taihang setinggi 200 meter dari Dek Observasi Tebing ✔️ Keajaiban buatan manusia di tebing ✔️ Lihat menara pengawas dari "Angkat Tanganmu" 📸 ✅ Hari ke-3: Mendaki Jalur Kuno Taihang di Gunung Timao - Grand Canyon Mendaki Huguan Taihang Grand Canyon, mendaki di sepanjang Jalur Bunga Persik, dan menikmati lautan awan ☁️ Menuruni Jalur Kuno Zhangyunti, melewati Puncak Manusia Raksasa dan Gerbang Hantu, dan bertemu dengan sekelompok kera liar! ✔️ Telusuri jalur rahasia Pegunungan Taihang yang berusia ribuan tahun ✔️ Pemandangan Grand Canyon yang menakjubkan ✅ D4: Jalan Kucing - Jembatan Alam - Ngarai Yinggu Jelajahi rute klasik Jalan Kucing Ngarai Yinggu di Pegunungan Taihang bagian barat, yang menampilkan anak tangga batu zig-zag yang terpahat di tebing! Tiba di jembatan lengkung batu alam terbesar di Tiongkok utara, [Jembatan Alam], dan jelajahi keajaiban gantung selebar 1 meter. Turun ke [Ngarai Yinggu], "Zhangjiajie dari Utara," dengan lanskap karst yang masih asli dan belum berkembang. ✔️ Seberangi rute off-road sepanjang 18 km, panjat "catwalk" dengan tangan dan kaki Anda. ✔️ Bermeditasi di Kuil Wanfo dan ambil foto-foto menakjubkan di Ngarai Yinggu 🏞️ ✅ D5: Shibanyan - Desa Pelukis - Kembali Jalan-jalan santai di [Desa Pelukis], dengan latar belakang pegunungan hijau dan aliran sungai yang gemericik, menawarkan kesempatan berfoto artistik 📷 [Desa Chuandi] Dikelilingi tebing, nikmati secangkir kopi dan berjemur di bawah Batu Shibanyan ☕ ✔️ Kota penuh warna yang terletak di bawah tebing batu merah ✔️ Akhir yang menenangkan dan fotogenik!ANSON SWANSON3Ini mungkin Grand Canyon 5AAAAA yang paling tidak populer di negara ini!
Ngarai Besar Longtan sungguh merupakan permata tersembunyi Luoyang. ✨ 1,2 miliar tahun sedimentasi geologis dan 2,6 juta tahun erosi air telah membentuk ngarai batu merah ini. Setiap foto adalah mahakarya! Dan jumlah pengunjungnya minimal, tanpa antrean. Sungguh pengalaman yang fantastis! 📍 Detail Lokasi Alamat: Kabupaten Xin'an, Kota Luoyang, Provinsi Henan (1,5 jam berkendara) Tips Parkir: Tersedia banyak tempat parkir di pintu masuk, 10 yuan/hari Jam Buka: 08.00 - 17.30 Tiket Masuk: 75 yuan/orang, gratis untuk anak-anak di bawah 1,2 meter Transportasi: 1,5 jam berkendara yang nyaman! Sangat direkomendasikan untuk berkendara sendiri! 🚗 ✨Panduan 3-4 jam 🛶 Naik bus wisata langsung ke "Alam Rahasia Danau Tianchi" → Jelajahi ngarai dengan perahu → Kembali ke halte bus 💦 Lanjutkan ke "Air Terjun Longtan" → Turuni gunung untuk menikmati pemandangan spektakuler di sepanjang jalan ✅ Lerengnya landai, sehingga mudah dinikmati baik dewasa maupun anak-anak. 🔥Lima tempat wisata wajib dikunjungi 1️⃣ Ngarai Batu Merah: Sebuah "kerutan waktu" yang tersisa di Bumi, dengan tebing-tebing yang menakjubkan ⛰️ 2️⃣ Kolam Air Jernih Dalam: Pemandangan menakjubkan dengan filter bawaan, dijamin menghasilkan foto 100%! 📸 3️⃣ Batu Tianbei: Sebuah mahakarya alam yang tak tertandingi, dengan bentuk-bentuk yang memukau ✨ 4️⃣ Air Terjun Longtan: Segarkan diri Anda seketika di tepi air di musim panas, pelarian sempurna dari panas ❄️ 5️⃣ Air mengalir ke atas: fenomena alam yang ajaib namun tidak realistis, yang menentang hukum fisika 🤯 ⚠️Tips Hematemesis Nyamuk banyak di pegunungan, jadi ingatlah untuk membawa obat nyamuk 🌿 Sepatu kets yang nyaman sangat penting 👟 Bawalah barang bawaan yang ringan! Jangan membawa terlalu banyak barang untuk jalur sepanjang 12 km ini. Waktu terbaik untuk berkunjung: Musim semi, musim panas, dan musim gugur (beberapa objek wisata tutup di musim dingin).ArtisticDreamer25Berangkat dari Luoyang! Keindahan Pegunungan Taihang Selatan membuat saya menimbun foto!
Keluarga, percayalah! Berangkat dari Luoyang menuju Xinxiang South Taihang Tourist Resort adalah perjalanan impian yang akan memukau feed media sosial Anda. Setelah check-in seperti yang direkomendasikan oleh National Geographic China, saya benar-benar terpikat oleh pemandangan menakjubkan di sepanjang jalan, dan memori album foto saya pun habis! Perhentian pertama kami adalah Longwan, di mana "Air Mata Biru" bahkan lebih menakjubkan dari yang saya bayangkan! Matahari bersinar, dan danau berkilauan seperti permata biru raksasa. Pilih hari yang cerah, arahkan ke "Dek Observasi Stasiun Penggembalaan Domba Jalan Xinxiang Baoshang," dan setiap foto akan menjadi mahakarya visual. Selanjutnya, kami tiba di "Jiangnan Kecil Pegunungan Taihang" yang dapat diakses gratis. Dengan vegetasi musim semi yang rimbun, kami berkemah dan barbekyu di sini, menikmati angin pegunungan yang menakjubkan, BBQ yang mendesis, dan pemandangan yang menakjubkan. Setelah petualangan yang melelahkan, kami menginap di salah satu B&B menakjubkan di dekatnya dan menikmati masa inap yang santai. Berikut rencana perjalanan berkendara mandiri satu hari dari Luoyang 👇 📍Pemberhentian 1: Berangkat dari Luoyang, berkendara ke Jalan Baoshang, dan nikmati keindahan Longwan. 📍Pemberhentian 2: Menuju Wujiawan dan rasakan pesona Desa Air Taihang. 📍Pemberhentian 3: Jelajahi Ngarai Besar Heimaogou dan rasakan keagungan alamnya. 📍Pemberhentian 4: Setelah Duohuo, lanjutkan perjalanan ke Doushui yang asri dan tenang. 📍Pemberhentian 5: Lewati Gua Diecai dan kembali dengan pemandangan yang menakjubkan. Jangan sia-siakan akhir pekan Anda di rumah! Ajak teman-teman dan mulailah perjalanan Anda dari Luoyang untuk tur berkendara mandiri di Pegunungan Taihang Selatan untuk menikmati keindahan pegunungan, sungai, danau, dan laut!AdventureLover3Tur 5 hari Henan Zhengzhou-Luoyang-Kaifeng cukup untuk menghemat uang dan menghindari jalan memutar yang tidak perlu.
Hai semuanya, bagaimana rencana perjalanan Anda ke Zhengzhou, Luoyang, dan Kaifeng di Henan? Itinerary 5 hari ini akan membawa Anda menjelajahi ketiga destinasi tersebut—pasti penuh tips, jadi simpan sekarang! -------------------- 📅 Itinerary Hari ke-1: [Eksplorasi Pertama Dataran Tengah] Tiba di Zhengzhou dan nikmati penjemputan yang ramah di bandara/stasiun. Nikmati hari penuh dengan waktu luang, jelajahi pesona pusat perbelanjaan. [Bermalam di Zhengzhou] Hari ke-2: Rasakan keindahan alam yang luar biasa melalui Kawasan Pemandangan Gunung Wanxian—dan kunjungi kembali Desa Guoliang, Desa Film dan Televisi Tiongkok, untuk merasakan perpaduan indah antara film dan televisi dengan alam. Hari ke-3: Jelajahi Kawasan Pemandangan Yuntaishan—berjalan-jalanlah melalui Ngarai Hongshi dan rasakan keajaiban alam—dan saat malam tiba, temukan hidangan lezat dan pesona kuno Jalan Tua Luoyang. Hari ke-4: Jelajahi Gua Longmen, temukan rahasia Kuil Qianxi dan area Gua Binyang yang berusia ribuan tahun—kagumi keagungan dan kesakralan Gua Teratai dan Buddha Vairocana—serta bangkitkan kerinduan Anda akan seni bela diri dan filosofi Zen Kuil Shaolin. Hari ke-5: Masuki Taman Tepi Sungai Qingming dan jelajahi kembali ke masa kejayaan Dinasti Song Utara. -------------------- Objek Wisata Wajib: Gua Longmen ⭐⭐⭐⭐⭐ Alamat: No. 13, Jalan Tengah Longmen, Distrik Luolong, Kota Luoyang, Provinsi Henan Jam Buka: 08.00 - 18.00 Durasi: 3-5 jam Harta karun seni berusia ribuan tahun ini menampilkan patung-patung Buddha yang memukau. Jangan lewatkan kesempatan ini. Taman Tepi Sungai Qingming ⭐⭐⭐⭐⭐ Alamat: No. 5, Jalan Longting Barat, Distrik Longting, Kota Kaifeng Jam Buka: 7 Oktober 2024 - 30 April 2025, pukul 09.00 - 16.30 Durasi: 1 hari Setiap langkah yang Anda ambil akan membawa Anda kembali ke Dinasti Song, tempat Anda dapat merasakan permainan kuno, mengagumi arsitektur kuno yang indah, dan menikmati pertunjukan rakyat. Kuil Shaolin ⭐⭐⭐⭐⭐ Alamat: Kawasan Pemandangan Shaolin Songshan, G207, Kota Dengfeng, Kota Zhengzhou, Provinsi Henan Jam Buka: 07.00 - 17.00 Durasi: 2-4 jam Merupakan leluhur Buddhisme Zen dan asal muasal seni bela diri. Kunjungan ke sini menawarkan budaya Zen yang mendalam dan apresiasi terhadap Kung Fu Shaolin, menjadikannya pengalaman yang sungguh berharga. -------------------- Tips Perjalanan: 📸 Spot Foto: Pelayaran Sungai Kuning Zhengzhou, Gua Longmen Luoyang, Taman Longting Kaifeng – jangan lewatkan pemandangannya! 🏷️ Harga Spesial Lokal: Bandingkan harga di berbagai lokasi, terutama Kue Kacang Kaifeng dan Kue Peony Luoyang. 🍜 Rekomendasi Kuliner: Zhengzhou Huimian, Luoyang Shuixi, dan Kaifeng Xiaolongbao yang wajib dicoba – biarkan lidah Anda menari! ✈️ Transportasi Bandara: Bandara Xinzheng Zhengzhou mudah diakses dari pusat kota dengan kereta api cepat atau bus. Kunjungi Henan dan rasakan keindahan sejarah dan alamnya! 🌺✨ -------------------- Perjalanan kami ke Zhengzhou, Luoyang, dan Kaifeng telah berakhir. Kami berharap dapat bertemu Anda kembali di lain waktu untuk menjelajahi lebih banyak keindahan Henan!Jaclyn Runte3HUIXIAN, provinsi Henan
Atraksi - Anda dapat menikmati pemandangan indah Gunung Baligou dan Tianjie, serta mendapatkan tiket. Anda juga bisa mendapatkan pemandu wisata dengan harga terjangkau. Saya sangat merekomendasikan pemandu wisata. Ia akan menemani Anda sepanjang hari. Anda juga bisa membeli tiket kereta gantung, tiket kereta api, dan tiket kereta antar-jemput. Pastikan Anda membeli tiket pulang pergi. Hotel - Ada banyak hotel di sekitar sini dengan harga yang sangat terjangkau, Anda juga bisa menikmati pemandian air panas di dekatnya. Makanan & Restoran - Anda bisa menemukan banyak restoran di pegunungan, makanan terbatas. Saya sarankan Anda juga membawa banyak makanan ringan dan air minum. #gunung #huixian #xinxiang #baligou #tianjie #perjalanan #penjelajah #cinaMimi Zondi94Tempat Check-in Baru di Baoquanyan Tianxia Telah Dibuka
Tempat check-in baru di Baoquanyan Tianxia kini telah hadir dengan kejutan! Musim dingin ini, jangan hanya di rumah saja, segera ajak teman-temanmu untuk berangkat bersama dan nikmati kebahagiaan musim dingin yang terbatas. Tempat check-in ini terletak di Baoquanyan Tianxia · Danya Tianlu · di samping Xinxin Xiangyin, di sini setiap langkah menyimpan kejutan. Kamu bisa melompat-lompat bersama teman di Danya Tianlu, satu detik terpesona oleh pemandangan yang megah, detik berikutnya tertawa bersama teman. Pipi yang memerah karena dingin dan uap napas yang keluar menjadi kenangan paling hidup musim dingin ini. Baoquanyan Tianxia sendiri sudah memiliki pemandangan alam yang unik, Danya Tianlu menambah keseruan petualangan. Di sini, kamu bisa merasakan keajaiban alam dan juga menikmati waktu bahagia bersama teman. Semua yang ingin mencari kebahagiaan di musim dingin, jangan lewatkan tempat check-in yang berharga ini. Segera ajak temanmu, datang ke sini dan buat kenangan musim dingin kalian, masih banyak tempat check-in dan foto yang menunggu untuk kamu jelajahi!Trip.PulseSalju Pertama Musim Dingin di Gunung Wanxian
Belakangan ini suhu terendah sangat rendah, Pegunungan Taihang beralih ke mode musim dingin, dan pemandangan salju di Gunung Wanxian sedang menunggu untuk terbentuk. Pemandangan salju di Gunung Wanxian sangat mempesona, ngarai tebing merah yang curam akan diselimuti embun beku perak, jalan gantung Guoliang yang merah dan putih bertabrakan menciptakan momen yang menakjubkan, puncak-puncak tajam tertutup salju putih, kabut berputar seperti lukisan tinta dan air yang mistis. Jalur pegunungan tertutup salju yang lembut, saat diinjak terdengar bunyi "krek", desa kuno dipenuhi dengan es dan salju putih, asap dapur mengepul, penuh dengan suasana musim dingin di pegunungan. Di sini, pengunjung dapat merasakan pengalaman musim dingin yang luar biasa, merasakan ketenangan dan penyembuhan di dunia yang diselimuti salju, dan bertemu dengan romantisme khas Taihang. Segera beli tiket, tunggu salju turun di Taihang, dan bergegas ke Gunung Wanxian!Trip.PulsePanduan Lengkap Rekomendasi Bǎoquán
Teman-teman! Saya menemukan sebuah tempat rahasia yang tersembunyi di Pegunungan Taihang 🌿 Rencana kabur dari kota di akhir pekan langsung terkunci di Bǎoquán, Henan! Air jernih dan pegunungan hijau + penginapan yang menyembuhkan, kebahagiaan yang bisa didapat hanya dengan biaya sekitar 200+ per orang, segera catat panduan ini! 💚 Tempat wajib dikunjungi di Bǎoquán yang "paling Instagramable" - Air Terjun Jiànlóng: Air terjun nomor satu di Taihang benar-benar membuat saya terkesan! Air mengalir dari ketinggian ratusan meter, kabut airnya seperti dunia peri~ Kenakan pakaian berwarna terang dan berdiri di balkon observasi untuk foto, dalam sekejap bisa menghasilkan foto dengan suasana yang luar biasa 📸 - Perahu Danau Bǎoquán: Harus naik! Perahu melaju di atas air yang jernih, pegunungan hijau di kedua sisi perlahan menjauh, angin membawa aroma tumbuhan, setiap jepretan seperti "Xiao Guilin" - Balkon Observasi Kaca: Bagi yang takut ketinggian harap hati-hati tapi benar-benar sangat Instagramable! Di bawah kaki adalah lembah yang luas, langit biru dan awan putih sebagai latar belakang, membuka kedua tangan untuk foto memberikan rasa kebebasan yang luar biasa~ 🏡 Temuan berharga! Penginapan Nánshě benar-benar mengerti para pelancong Awalnya saya bingung memilih penginapan saat membuat panduan, tapi setelah menginap di Nánshě langsung jadi penggemar! Hanya 5 menit berjalan kaki ke pintu masuk kawasan wisata Bǎoquán, tidak perlu bangun pagi dan buru-buru naik kendaraan, sangat nyaman! - Kamar dengan tampilan menarik: Kami memesan kamar twin dengan pemandangan gunung, membuka jendela langsung melihat pemandangan hijau yang segar 🌳 Dekorasi bergaya kayu alami + dekorasi lembut ala Instagram, perlengkapan tempat tidur lembut seperti di rumah, bahkan perlengkapan mandi bebas silikon, detailnya sangat diperhatikan! Layanan yang sangat perhatian: Tempat parkir gratis, bagi yang datang dengan mobil pribadi tidak perlu khawatir sama sekali! Memilih penginapan yang tepat bisa menambah banyak kesenangan dalam perjalanan, penginapan Nánshě ini pasti pilihan yang bagus saat kamu datang ke Bǎoquán~楠舍民宿(輝縣寶泉旅度假區店)Guoliang Cliffside Highway: Sebuah perjalanan melalui sejarah sinematik 20 tahun "Raise Your Hands".
Tahun ini menandai peringatan 20 tahun film klasik "Raise Your Hands", dan Jalan Raya Tebing Guoliang di Kawasan Pemandangan Wanshanshan, Pegunungan Taihang Selatan di Xinxiang, tempat film ini difilmkan, menyimpan kenangan indah dari berbagai generasi. Koridor tebing buatan manusia ini, yang dikenal sebagai "Keajaiban Dunia Kesembilan", terkenal dengan adegan-adegan kocaknya, seperti "Paman Guo menggiring keledainya melintasi tebing, dan tentara Jepang berkaki busur memanjat jalan raya." Ketika sosok-sosok familiar melangkah ke "koridor tebing" dan menyentuh bekas pahatan berbintik-bintik di permukaan batu, kenangan pahit-manis dari film tersebut langsung mengalir kembali, seolah waktu telah berputar kembali. Pengunjung dapat menirukan postur Paman Guo yang tenang menggiring keledainya di bawah jendela atap di tengah Jalan Raya Tebing Guoliang dan merasakan kembali adegan klasik dari film tersebut. Yang lebih menarik lagi, "Raise Your Hands 3" telah memulai praproduksi, dan cerita barunya akan tetap berlatar di Pegunungan Taihang Selatan. Pengunjung dapat memanfaatkan musim dingin ini untuk memenuhi janji sinematik 20 tahun ini, menyusuri jalan raya di tepi tebing yang ditampilkan dalam film, mendengarkan penduduk desa bercerita di balik layar proses syuting, merasakan semangat Guoliang—"Pria Tua Bodoh Baru yang Memindahkan Gunung"—dan menemukan kembali kegembiraan masa kecil di tengah pemandangan megah Pegunungan Taihang. Datanglah ke Gunung Wanshan dan biarkan janji 20 tahun ini berakhir dengan sempurna!Trip.PulsePegunungan Taihang yang megah membentang sejauh delapan ratus mil, mencakup sejarah dua ribu tahun.
Panduan Pendakian Gunung Taihang Selatan Pegunungan Taihang Selatan menawarkan kemegahan dan keindahan, dengan tebing-tebing yang menjulang tinggi serta kolam dan air terjun yang saling terhubung. Disertifikasi oleh *Geografi Nasional Tiongkok* sebagai destinasi pendakian klasik, rute-rutenya sudah mapan dan memiliki tingkat kesulitan sedang, cocok untuk pendaki pemula maupun berpengalaman. Fokus utamanya adalah ngarai, desa-desa kuno, dan pemandangan tebing yang spektakuler. Berikut panduan singkat dan praktisnya. I. Waktu Pendakian Terbaik Waktu Inti: Mei-Oktober (Disarankan) • Mei-Juni: Hutan yang rimbun, kolam yang jernih, dan cuaca sejuk tanpa panas ekstrem; • September-Oktober: Warna-warna musim gugur yang melimpah, pemandangan yang luas, dan kemungkinan besar bertemu lautan awan, menghasilkan peluang foto yang luar biasa; • Tips Penghindaran: Kekurangan air dan kondisi es di musim dingin; pemandangan relatif monoton di bulan Maret-April; Disarankan untuk berhati-hati selama musim hujan (akhir Juli-Agustus), karena bagian ngarai licin dan berisiko. II. Rute Klasik yang Direkomendasikan 1. Rute Esensial 2 Hari yang Ramah Pemula (Mudah Difoto) • Hari ke-1: Xinxiang → Mawuzhai → Qixingtan → Desa Baodu (Bermalam) Sekitar 10 km, 4-5 jam, dengan tanjakan 600 m. Melintasi hutan dan ngarai, mengunjungi Qixingtan yang masih asli dan "Surga Tebing" Desa Baodu. Rutenya sebagian besar datar, dengan sedikit pijakan di sepanjang tepi ngarai. • Hari ke-2: Desa Baodu → Yixiantian (One Line Sky) → Baligou → Perjalanan Pulang Sekitar 8 km, 3-4 jam, dengan tanjakan 200 m. Melewati Yixiantian (Langit Satu Garis) yang menantang, akhirnya mencapai Area Pemandangan Baligou, mengunjungi Air Terjun Tianhe. Setelah itu, naik bus area pemandangan atau sewa mobil kembali ke Xinxiang. 2. Itinerary Panorama Mendalam 5 Hari (Mencakup Tempat-Tempat Pemandangan Utama) • Hari ke-1: Xinxiang → Shuangdi → Mawuzhai (Bermalam), sekitar 5 jam pendakian, menghindari area yang sudah dibangun, menyusuri jalur tebing, dan menikmati pemandangan lembah yang asri; • Hari ke-2: Mawuzhai → Desa Baodu → Baligou → Huilong (Bermalam), 7-8 jam, berfokus pada pengalaman Langit Satu Garis Baodu dan keajaiban alam Baligou; • Hari ke-3: Huilong → Zhanggou (Bermalam), sekitar 5 jam pendakian, termasuk berjalan kaki melalui Jalan Raya Tebing Huilong dan mendaki ke puncak Puncak Laoye untuk menikmati panorama pegunungan; • Hari ke-4: Zhanggou → Shiziling → Wangmangling (Bermalam), 9 jam pendakian melalui bagian inti Shuangling, dan menyaksikan matahari terbenam di Wangmangling di sore hari; • Hari ke-5: Wangmangling → Desa Guoliang → Xinxiang, sekitar 5 jam pendakian, mengunjungi Jalan Raya Tebing Guoliang dan pusat film dan televisi, mengakhiri perjalanan pulang. III. Objek Wisata Utama yang Wajib Dikunjungi • Desa Baodu: Desa kuno terakhir di Shanxi yang tidak memiliki akses jalan. Air Terjun Laolongkou sangat memukau selama musim hujan. Desa ini memancarkan pesona pedesaan yang semarak dan merupakan permata tersembunyi bagi para pendaki. • Baligou: Area pemandangan 5A. Air Terjun Tianhe disebut-sebut sebagai "Jiwa Taihang." Gua tirai air dan kolam yang saling terhubung menciptakan konsentrasi lanskap alam yang padat. • Wangmangling: Menampilkan lautan awan dan puncak-puncak yang terjal, Anjungan Pengamatan Matahari Terbit adalah tempat terbaik untuk menikmati matahari terbit di Pegunungan Taihang selatan. Pagi-pagi sekali menawarkan lebih sedikit keramaian dan pemandangan yang menakjubkan, dengan puncak-puncak yang berkilauan warna-warni. • Jalan Raya Tebing Guoliang: Keajaiban buatan manusia. Anjungan Pengamatan Desa Tebing adalah tempat terbaik untuk fotografi, mengabadikan bidikan sempurna jalan raya di sepanjang tebing terjal. IV. Transportasi dan Akomodasi 1. Panduan Transportasi • Transportasi Eksternal: Prioritaskan tiba di Stasiun Xinxiang/Stasiun Xinxiang Timur. Xinxiang adalah pusat pendakian di Pegunungan Taihang Selatan. Menyewa mobil ke dan dari tempat-tempat wisata adalah pilihan yang paling nyaman (hemat biaya dengan transportasi bersama). Wisatawan tunggal dapat beralih ke bus ke Huixian dan kemudian bus antar-jemput ke area wisata. • Transportasi Dalam Kota: Tidak ada bus langsung antar area wisata. Rute pendakian utamanya berjalan kaki. Di dalam area wisata, bus wisata tersedia sesuai kebutuhan (bus berbayar/kereta gantung tersedia di area wisata Huilong dan Wanxianshan; opsional). 2. Rekomendasi Akomodasi • Kota Xinxiang: Menginaplah di sini malam sebelum pendakian Anda. Terdapat banyak pilihan hotel dengan fasilitas lengkap, sehingga memudahkan Anda untuk berangkat pagi-pagi keesokan harinya. • Akomodasi Pegunungan: Sebagian besar berupa wisma/penginapan sederhana (Mawuzhai, Desa Baodu, Zhanggou, dll.). Kondisinya sederhana dan bersih, dengan harga 80-150 yuan per malam. Beberapa daerah dataran tinggi (seperti Zhanggou) mengalami kekurangan air di musim dingin; prioritaskan akomodasi dengan pasokan air yang andal. • Wangmangling: Hanya Hotel Lingyun yang menyediakan makanan dan penginapan. Mohon konfirmasi status buka terlebih dahulu untuk menghindari kekurangan akomodasi. V. Perlengkapan dan Tindakan Pencegahan Penting 1. Perlengkapan Inti • Pakaian: Sepatu hiking antiselip (penting untuk area tanah/licin), pakaian cepat kering, pelindung lutut, topi/jaket hangat (perbedaan suhu yang besar di daerah pegunungan); • Peralatan: Tongkat hiking (untuk mengurangi tekanan pada lutut), lampu kepala (untuk mengantisipasi keterlambatan), power bank, dan tabir surya; • Perlengkapan: Air minum (2-3 liter per orang per hari), camilan berenergi (kacang, cokelat), membawa satu bekal makan siang (tidak perlu diisi ulang di beberapa area), dan obat-obatan umum (plester, obat maag, obat mabuk perjalanan). 2. Tindakan Pencegahan Utama • Pengingat Biaya: Biaya masuk Huilong adalah 60 yuan; biaya masuk Wanxianshan + paket bus adalah 125 yuan. Beberapa jalur yang jarang dilalui mungkin memiliki biaya sementara; Siapkan uang tunai atau pembayaran seluler terlebih dahulu. • Identifikasi Rute: Saat melintasi jalur setapak, prioritaskan bagian yang lebar. Botol air dan rambu-rambu jalur merupakan penanda penting. Pemula disarankan untuk tetap bersama rombongan atau menggunakan peta pendakian offline; jangan menjelajahi jalur yang belum dikenal sendirian. • Aturan Perlindungan Lingkungan: Bawalah semua sampah Anda; tidak ada tempat sampah di pegunungan. Lindungi ekosistem yang masih asli. • Utamakan Keselamatan: Setelah hujan, jalur setapak (terutama "jalur setapak" batu kapur) sangat licin; gunakan rantai untuk melewatinya. Jika cuaca buruk, segera turun. Staf dapat dihubungi untuk membantu di area pemandangan kapan saja.CelestialDreams511Musim Dingin di Guoliang | Saat salju menutupi Pegunungan Taihang, saya mendengar batu-batu bernapas!
Hari ketika saya memasuki pegunungan, salju turun tanpa suara. Setelah melewati Huixian, kabut menebal, hamparan putih menyelimuti siluet pegunungan hijau tua, bagaikan lukisan tinta setengah jadi yang digoyangkan pelan. Navigasi telah lama gagal, jadi saya mengikuti dua jejak dangkal yang ditinggalkan mobil di depan saya, berkelok-kelok ke atas—bukan ke tempat yang indah, melainkan untuk menepati janji lama dengan tebing. Di pintu masuk Desa Guoliang, sebuah kilang batu terhampar tenang di atas salju. Tidak ada turis yang terlihat, hanya seorang lelaki tua bermantel katun biru tua, perlahan-lahan menyapu salju dari batu kilangan. Batu kilangan itu kasar, saljunya setengah mencair, tetesan air menetes perlahan dari alurnya, mengetuk lembut tanah yang beku. Dia menatap saya, tidak bertanya dari mana saya berasal, melainkan hanya menunjuk ke belakangnya: "Pintunya terbuka; angin juga masuk." Pintu itu adalah pintu masuk Terowongan Guoliang, yang terukir di tebing—tanpa gapura, tanpa gerbang tiket, hanya sebuah bukaan melengkung gelap yang menanjak, bagaikan luka yang tenang namun mendalam yang terukir di bumi oleh Pegunungan Taihang itu sendiri. Di dalam Terowongan Guoliang, debu dan cahaya melayang dalam sorotan senter. Saya mematikan navigasi ponsel dan menyalakan senter saku. Sinar itu menembus kegelapan, dan dalam sekejap, butiran debu yang tak terhitung jumlahnya naik, berputar-putar, dan melayang— Mereka tidak melayang, melainkan berenang, seperti plankton laut dalam, diam-diam bermigrasi di antara bekas pahatan berusia berabad-abad di permukaan batu. Ujung jari saya menyentuh dinding terowongan; terasa kasar dan menyakitkan, namun hangat. Pemandu kami, Xiao Yang, berkata, "Saat itu, tiga belas keluarga, dengan mengandalkan penusuk dan palu baja, menghabiskan lima tahun mengukir sepanjang 1.200 meter." Saya tidak berbicara, hanya dengan lembut menyandarkan dahi saya ke batu. Saat itu, yang kudengar bukanlah gema, melainkan denyutan pelan dan terus-menerus yang berasal dari kedalaman batu—gunung yang paling keras, ternyata, memiliki detak jantung; musim dingin terdingin, ia menyimpan kehangatan. Tebing Tangga Surgawi, sebuah jalan setapak sempit yang menggantung di atas garis salju. Dari dalam gua, muncullah Tangga Surgawi. Itu bukanlah jalan setapak kayu yang dibangun oleh kawasan wisata, melainkan jalan setapak sempit berlapis es yang dihaluskan oleh penduduk setempat, nyaris tak cukup lebar untuk dilewati satu orang. Di sebelah kiri terdapat tebing terjal, di sebelah kanan jurang yang dalam, es tipis dan salju di bawah kakiku berkilau tajam. Seembusan angin tiba-tiba menerbangkan kepingan salju yang menyengat bulu mataku. Aku berhenti, menatap napasku sendiri, gumpalan uap putih, lebih ringan dari awan di bawah kakiku, lebih tangguh dari pohon pinus layu di tepi tebing. Saat itu, seekor burung pipit gunung terbang melintasi jurang, sayapnya mengaduk udara. Ia tak bernyanyi, ia hanya terbang—mengukur kehampaan yang tak berani manusia tatap langsung dengan tubuhnya yang mungil. Tiba-tiba aku tersenyum: Ternyata ketika manusia berdiri di celah sempit antara langit dan bumi, itu bukan untuk menaklukkan ketinggian, melainkan untuk menegaskan diri, untuk menegaskan bahwa mereka masih berani bernapas. Sebuah lahan pengirikan gandum desa tua, kesemek beku, dan sepucuk surat yang belum dibuka dari rumah. Lahan pengirikan gandum desa itu kosong, beberapa tumpukan jagung berselimut salju, seperti raksasa cokelat yang meringkuk. Seorang perempuan tua duduk di bawah atap, mengupas kenari, keranjang penampinya penuh dengan kulit ari hijau. Jari-jarinya merah karena dingin, namun lincah seperti kupu-kupu. Melihatku memotret, ia membuka telapak tangannya, memegang tiga kesemek beku: "Mau coba?" Aku menggigit satu; Esnya pecah, rasa asam dan sepat menyerbu hidungku, tetapi kemudian rasa manis seperti madu menyebar di lidahku— Pegunungan dan ladang telah mengubah dingin yang menusuk menjadi manis. Cucunya berlari keluar rumah, menyerahkan sepucuk surat yang belum terkirim: "Nenek menulis ini untuk putranya yang bekerja di kota, takut kantor pos tutup..." Tulisan tangan di amplop itu miring, tintanya agak kabur karena angin yang merembes masuk melalui celah-celah jendela. Aku membantunya menempelkan perangko dan memasukkannya ke dalam kotak surat hijau berkarat di pintu masuk desa. Lubang kotak surat itu dalam dan gelap, seperti sumur kecil yang dipenuhi kerinduan. Sebelum kembali, aku duduk di anjungan pandang di sisi jalan tebing. Matahari terbenam, melelehkan emas, memercik ke tebing di seberang. Es-es menggantung seperti tirai kristal, pegunungan yang tertutup salju menyerupai duri naga perak. Dan di bawahnya, jalan di sisi tebing, tergantung di tebing, meliuk-liuk seperti benang perak yang berkilauan dan belum sembuh. Saya tidak memotret kemegahannya, hanya sebuah es di celah: Tajam, transparan, namun di dalamnya hanya sehelai rumput layu dan daun gugur— Sama seperti kita: Meskipun hidup telah menajamkan sisi-sisi kita, kita masih diam-diam melindungi secercah hijau di hati kita. Salju berhenti turun saat kami menuruni gunung. Lampu depan mobil menembus senja, dan dalam sorotan cahaya, kepingan salju halus mulai berjatuhan lagi, lembut, perlahan, tanpa keributan atau persaingan. Ternyata Guoliang di musim dingin tidak pernah berusaha menyenangkan siapa pun dengan gembar-gembor. Guoliang hanya mengubah batu berusia ribuan tahun, salju berusia berabad-abad, dan keheningan selama puluhan tahun menjadi satu tekstur—kehangatan dalam kekerasannya, ketenangan di ketinggiannya, dan napas yang bersemangat dan tak kenal lelah di padang gurunnya yang tandus.Charlotte WorthingtonPendakian musim dingin di Pegunungan Taihang Selatan: Kerajaan es dan salju sungguhan, sangat indah.
👋Inti dari Pegunungan Taihang terletak di Pegunungan Taihang Selatan. Waktu paling menakjubkan untuk mengunjungi Pegunungan Taihang Selatan adalah musim dingin! ❄️Keajaiban musim dingin yang sesungguhnya tersedia untuk waktu terbatas! Jamur es, gua es biru, air terjun es pinus yang tertutup salju… ✔️Rasakan keindahan musim dingin terbatas dalam 3 hari~ Siapa bilang musim dingin berarti di rumah saja? Musim dingin di Pegunungan Taihang Selatan adalah surga bagi para penggemar hiking! Berjalan di antara salju tebal, berkelok-kelok di antara air terjun es dan pohon pinus yang tertutup salju, setiap langkah terasa seperti melangkah ke dunia dongeng. Pengalaman musim dingin yang imersif ini sungguh adiktif! 🌟【Rute Pendakian 3 Hari 2 Malam】Pengalaman Imersif Mengungkap Keajaiban Musim Dingin Hari ke-1: Area Pemandangan Wanshanshan → Air Terjun Es Pinus Salju Zhonghua → Desa Guoliang • Pagi: Tiba di Area Pemandangan Wanshanshan dan naik bus menuju titik awal pendakian. Area pemandangan ini jarang penduduknya di musim dingin, dan jalur pegunungannya tertutup salju, dengan pepohonan yang dihiasi cabang-cabang berselimut salju seperti untaian mutiara putih. • Sore: Mendaki ke "Air Terjun Es Pinus Salju Cina", sebuah landmark Pegunungan Taihang Selatan di musim dingin. Air terjun es setinggi 30 meter mengalir menuruni tebing, dengan es, tirai es, dan bunga es yang saling bertautan, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Sinar matahari yang terpantul dari air terjun es menciptakan kaleidoskop warna. Pastikan untuk mengambil foto dari platform pengamatan di bawah air terjun es; Berdiri di dekatnya, Anda benar-benar dapat merasakan kekuatan alam yang menakjubkan. • Malam: Menginap di wisma di Desa Guoliang. Rumah-rumah batu di desa ini tertutup salju, menyerupai kastil-kastil kecil. Di malam hari, Anda dapat berkumpul di sekitar perapian untuk menikmati hidangan hangat dan lezat khas pertanian, termasuk ayam rebus, jamur liar tumis, dan kue jagung—pengalaman yang sungguh menenangkan. Hari ke-2: Desa Guoliang → Ngarai Tongtian → Desa Pelukis • Pagi: Berangkat dari Desa Guoliang dan mendaki ke "Ngarai Tongtian." Rute pendakian ini memiliki tingkat kesulitan sedang, dengan pemandangan menakjubkan di sepanjang jalan. Aliran air di ngarai telah membeku, membentuk kolam es sebening kristal. Es memantulkan pegunungan dan pepohonan di kedua tepiannya, menciptakan lukisan cat minyak yang indah. • Sore: Jelajahi formasi "jamur es" di Ngarai Tongtian. Jamur es ini, yang terbentuk secara alami oleh es dan salju, hadir dalam berbagai bentuk, beberapa menyerupai payung kecil, yang lainnya seperti kastil—mereka sangat imut. Untuk berfoto, cobalah berjongkok untuk mendapatkan sudut rendah; ini akan menciptakan efek yang unik. Setelah itu, lanjutkan pendakian ke "Desa Seniman". • Sore: Tiba di Desa Seniman, sebuah desa kecil yang menawan dan penuh dengan suasana artistik. Di musim dingin, desa ini diselimuti salju, rumah-rumah berwarna-warni di antara lapisan salju tebal menyerupai kota dongeng. Berjalan-jalanlah menyusuri desa dan kagumi karya-karya seniman lokal. Hari ke-3: Desa Seniman → Perjalanan Pulang • Pagi: Bangun dengan cahaya pagi di Desa Seniman. Buka jendela Anda untuk melihat pemandangan salju yang indah. Berjalanlah di sepanjang jalan setapak desa, hirup udara segar, dan rasakan ketenangan pegunungan. Jika beruntung, Anda bahkan mungkin melihat matahari terbit. Matahari terbit di balik pegunungan, memancarkan sinar matahari keemasan ke atas salju—pemandangan yang sungguh spektakuler. • Siang: Setelah makan siang di desa seniman, bersiaplah untuk kembali. Ini adalah penutup perjalanan musim dingin Anda yang tak terlupakan di Pegunungan Taihang Selatan. 📸【Tips Fotografi Hiking】 1. Manfaatkan kontras lingkungan: Kenakan pakaian berwarna cerah (merah, kuning, biru) untuk menciptakan kontras yang kuat dengan salju dan es putih, menghasilkan foto yang menarik perhatian. 2. Abadikan momen dinamis: Berlari dan melompatlah di atas salju dan mintalah seorang teman untuk memotret; ini akan menghasilkan foto yang hidup. 3. Potret detail dari dekat: Abadikan detail seperti bunga es di air terjun es, jejak kaki di salju, dan embun beku di dahan untuk menambah kedalaman dan dimensi pada foto Anda. 🧥【Saran Pakaian Hiking】 • Alas Kaki: Pastikan untuk mengenakan sepatu hiking atau sepatu salju dengan daya cengkeram yang baik agar tidak terpeleset di permukaan es. • Pakaian: Gunakan metode "onion layering": kenakan pakaian dalam termal yang cepat kering sebagai lapisan dalam, bulu domba atau sweter sebagai lapisan tengah, dan jaket tahan angin dan tahan air atau jaket bulu angsa sebagai lapisan luar. • Aksesori: Kenakan topi Lei Feng atau topi wol, syal tebal, dan sarung tangan tahan air agar tetap hangat dan bergaya. 💡【Tindakan Pencegahan Pendakian】 • Periksa prakiraan cuaca terlebih dahulu dan pilih hari yang cerah untuk mendaki. • Lakukan pemanasan sebelum mendaki untuk menghindari cedera. • Bawalah makanan dan air yang cukup untuk mengisi kembali energi. • Jangan meninggalkan jalur pendakian agar tidak tersesat. • Hati-hati; kurangi kecepatan dan hindari terpeleset di permukaan es. Pegunungan Taihang Selatan di musim dingin sungguh patut dikunjungi! Ajak teman-teman Anda dan rasakan kerajaan es dan salju yang sesungguhnya!Wanderlust Foodie【Simpan keindahan Baoquan dalam lensa kameramu】
Ketika kabut pagi Baoquan menyelimuti perbukitan hijau, ketika aliran sungai mengalunkan melodi gemericik di antara bebatuan, ada sebuah tempat bernama "Yundu" yang mengubah pesona alam resor menjadi pemandangan sehari-hari yang bisa dilihat hanya dengan membuka jendela — Yundu Homestay (Cabang Resor Wisata Baoquan), sebuah tempat tinggal yang bisa memenuhi lensa Momen Trip-mu dengan puisi. Tak perlu mencari bingkai foto dengan sengaja, setiap langkah di Yundu adalah momen yang memikat hati. Pagi hari saat membuka pintu teras kayu, pemandangan pegunungan dan air Baoquan yang diselimuti kabut tipis perlahan terbangun, puncak gunung berwarna abu-abu kebiruan menopang matahari terbit berwarna oranye, angin pegunungan membawa aroma segar tumbuhan menyapu wajah, saat itu tekan tombol rana sesukamu, baik close-up rambut yang terkena cahaya balik maupun pemandangan orang dengan latar gunung jauh, semuanya seperti adegan yang keluar dari lukisan tinta Cina. Menginap di Yundu bukan sekadar "tinggal", tapi menjadikan perjalanan sebagai waktu yang santai. Sore hari duduk di tempat minum teh dengan pemandangan di homestay, seduh secangkir teh lokal, lihat bayangan cahaya yang bertebaran di atas meja, cangkir teh, halaman buku, dan pemandangan gunung di kejauhan saling melengkapi, setiap frame adalah potongan kehidupan yang menenangkan. Yang lebih istimewa, Yundu Homestay memiliki kemudahan "dekat dengan air" — hanya berjalan kaki untuk mencapai titik utama Resor Wisata Baoquan, jika tidak ingin berjalan kaki, bisa menghubungi homestay sebelumnya untuk mendapatkan layanan antar-jemput gratis ke area wisata!! Tanpa harus terburu-buru, kamu bisa dengan mudah menangkap keindahan air terjun yang mengalir deras dan kolam dalam berwarna hijau jernih. Di Yundu Homestay (Cabang Resor Wisata Baoquan), Momen Trip bukan lagi sekadar "rekaman check-in", melainkan dialog lembut dengan gunung, air, dan waktu. Setiap jendela, setiap sudut, setiap pemandangan di sini menunggu kamu menekan tombol rana, menyimpan keindahan Baoquan dalam lensa kameramu. Homestay: Yundu Homestay (Cabang Resor Wisata Baoquan) Alamat: No. 98, Desa Dongshenzhuang, Kota Bobo, Huixian雲度民宿(寶泉旅遊度假區店)Perjalanan Menjelajahi Keajaiban Pegunungan Taihang: Panduan Lengkap ke Gunung Wanshan di Henan
Gunung Wanshan di Provinsi Henan terletak jauh di Pegunungan Taihang. Pegunungan di sana berwarna merah, jalanannya berpadu dengan tebing, dan kisah-kisahnya dipahat dari generasi ke generasi. Saya punya panduan langsung yang segar di sini, berdasarkan pengalaman pribadi dan kisah-kisah lokal, dijamin akan memberikan Anda perjalanan yang autentik dan menyenangkan. Perhentian Pertama: Bagaimana Menuju ke Sana? Gunung Wanshan sebenarnya adalah kawasan wisata yang luas, sebagian besar terbagi menjadi Desa Guoliang dan Nanping. Terlepas dari titik awal Anda, pilihan terbaik adalah pergi ke Xinxiang terlebih dahulu. Naik kereta cepat ke Stasiun Xinxiang Timur, atau kereta reguler ke Stasiun Xinxiang. Setelah Anda keluar dari stasiun, jangan panik. Anda punya dua pilihan: Pertama, naik bus langsung dari Terminal Bus Xinxiang ke kawasan wisata (biasanya ke "Kotapraja Shayao" atau "Kawasan Wisata Gunung Wanshan"). Perjalanan memakan waktu sekitar dua jam, sebagian besar melalui jalan pegunungan yang berkelok-kelok, jadi bagi yang rentan mabuk perjalanan sebaiknya menyiapkan obat terlebih dahulu. Kedua, berbagi tumpangan dengan beberapa orang lain; Anda akan langsung diantar ke pintu masuk area wisata, menghemat waktu dan tenaga, dan biaya per orangnya pun terjangkau. Ingat, jika Anda berkendara, pastikan untuk mengatur navigasi ke "Tempat Parkir Area Wisata Wanshanshan." Tempat parkir jarang tersedia selama musim ramai, jadi datanglah lebih awal. Perhentian Kedua: Menginap? Makan Apa? Saya sangat merekomendasikan untuk menginap di dalam area wisata, terutama di Desa Guoliang! Dengan cara ini, Anda dapat merasakan ketenangan total, pelarian sejati dari hiruk pikuk dunia. Sebagian besar akomodasi di desa ini adalah wisma yang dikelola keluarga—sederhana namun bersih. Buka jendela Anda untuk menikmati pemandangan tebing terjal—sensasinya sungguh luar biasa. Pemiliknya umumnya sangat jujur dan lugas; jangan ragu untuk bertanya. Makanlah di wisma Anda dan cicipi hidangan otentik bergaya pertanian Gunung Taihang: salad seledri liar segar, telur tumis yang harum, jamur gunung rebus yang lezat, dan mi buatan tangan—dijamin akan memuaskan Anda. Harganya terjangkau, dan porsinya besar. Perhentian Ketiga: Aktivitas Apa yang Harus Dilakukan? Inilah daya tarik utamanya! Inti dari Wanshanshan terletak setengah pada "jalannya yang unik" dan setengah lagi pada "lembah-lembah terpencilnya". 1. Desa Guoliang—Legenda di Tebing Datang ke Wanshanshan tanpa melihat jalan di sisi tebing adalah perjalanan yang sia-sia! Jalan ini, yang dikenal sebagai "Keajaiban Dunia Kesembilan", dipahat dari tebing batu merah oleh 13 pria dari Desa Guoliang selama lima tahun menggunakan pahat dan palu baja. Berjalan di sepanjang jalan ini, sambil memandangi jurang terjal melalui "jendela" di satu sisi, rasa takjub yang tak terlukiskan. Saya merekomendasikan untuk mendaki seluruh jalan di sisi tebing sepanjang 1,2 kilometer untuk perlahan-lahan menghargai keberanian para leluhur kita. Setelah mendaki jalan di sisi tebing, kunjungi desa tua Guoliang, dengan rumah-rumah batu kuno dan lapuknya. Film "Raise Your Hand" difilmkan di sini. Dua titik pandang yang sayang untuk dilewatkan: Tianchi (waduk tinggi yang indah) dan rumah-rumah di tepi tebing, yang menawarkan panorama jalan di tepi tebing yang luar biasa indahnya saat matahari terbit dan terbenam. 2. Nanping – Sebuah Lukisan Lanskap Berbeda dengan nuansa historis Guoliang, Nanping lebih seperti lukisan lanskap yang semarak. Jantung kawasan ini adalah Danfengou, jalur ngarai yang sangat menyegarkan. Berjalan di sepanjang aliran sungai dan air terjun, suasana teduhnya terasa menenangkan di musim panas. Air Terjun Kolam Naga Hitam di puncaknya menderu dengan semburannya yang kuat, sebuah pengalaman yang sungguh menenangkan. Jalur pegunungan di sisi Nanping agak melelahkan, tetapi pemandangannya sepadan dengan harga tiket masuknya. Terakhir, beberapa tips bermanfaat: * **Alokasi Waktu:** Alokasikan setidaknya dua hari penuh. Satu hari untuk Guoliang, satu hari untuk Nanping, agar Anda dapat bersantai tanpa terburu-buru. * **Musim Terbaik:** Akhir musim semi hingga awal musim gugur (April-Oktober) sangat fantastis. Musim semi menghadirkan bunga-bunga liar yang semarak, musim panas menawarkan kesejukan dari terik matahari, dan musim gugur mewarnai hutan dengan warna-warna yang menakjubkan. Beberapa bagian jalur pendakian mungkin ditutup pada musim dingin. * **Perlengkapan Penting:** Sepatu yang nyaman dan antiselip (penting untuk mendaki), tabir surya, topi (sinar UV yang kuat di pegunungan), dan jaket tipis (pagi dan sore hari yang sejuk). Jangan lupa kamera dan power bank Anda; ada begitu banyak keindahan yang bisa diabadikan hingga baterai ponsel Anda mungkin habis. * **Pola Pikir:** Ini bukan kota yang ramai; Anda akan menikmati alam dan ketenangan. Penduduk setempat ramah, dan harga-harganya transparan, sehingga Anda dapat bepergian dengan tenang. Keindahan Gunung Wanshan yang terjal sekaligus lembut, keindahan yang menghadirkan rasa damai. Ambil panduan ini dan berangkatlah! Saya jamin setelah Anda kembali, Anda akan memimpikan Gunung Taihang merah yang megah itu!williamvolcanoRahasia Baliyigou! Menginap di Rumah Dewa
Melarikan diri dari hiruk-pikuk kota besar di akhir pekan, saya dan sahabat mengemudi ke kawasan wisata Baliyigou di Nan Taihang, Xinxiang. Tempat ini dijuluki "Jiwa Taihang", ketenangan di antara gunung dan air membuat lelah sehari-hari langsung hilang. Kami menginap di Bailie Yisu Shisu, sebuah penginapan kecil dan indah di tepi danau yang tersembunyi di dekat Air Terjun Taohuawan, benar-benar penuh kejutan! 🌟🌲 🏡 Rumah pelarian di hutan pegunungan yang tenang 🌿 Saat tiba, saya langsung terpesona oleh pemandangan di depan mata. Penginapan ini terletak di tengah hutan pegunungan yang sunyi, setiap jendela adalah bingkai lukisan alam, di luar jendela terlihat pegunungan yang bergelombang, kabut melayang, seolah berada di dunia peri. Desain kamar sederhana dan elegan, setiap detail menunjukkan perhatian pemiliknya. Duduk di tepi jendela sambil menikmati secangkir teh, melihat pemandangan danau dan gunung di kejauhan, waktu seakan berhenti. 🍵 🛁 Ruang pribadi yang nyaman 🛋️ Bagian dalam kamar sangat nyaman, dilengkapi dengan shower, sikat gigi, kamar mandi pribadi, sampo, dan pemanas ruangan, semua fasilitas sangat modern namun tetap harmonis dengan lingkungan alam. Yang paling saya suka adalah tempat tidur besar itu, empuk dan pas, tidur malam sangat nyenyak, bangun pagi hari merasa segar dan bugar. 🌙 🏞️ Lokasi terbaik untuk menikmati gunung, awan, dan danau 🏞️ Yang paling tak terlupakan adalah pemandangan dari kamar, baik pagi maupun sore, selalu ada keindahan yang berbeda. Di pagi hari, kabut perlahan naik di antara gunung, seluruh dunia tertutup oleh selubung misterius; di sore hari, sinar matahari terbenam memantul di permukaan danau, berkilauan keemasan, sangat memukau. Pemandangan seperti ini benar-benar membuat enggan pergi. 🌅 🍽️ Hidangan lezat di tengah alam 🍽️ Selain pemandangan, makanan di sini juga menjadi daya tarik utama. Restoran menyajikan hidangan khas lokal dengan bahan segar dan cara memasak otentik, setiap hidangan membuat lidah bergoyang. Terutama sup ayam dengan jamur liar, kuahnya lezat, daging ayamnya lembut, setiap suapan adalah kenikmatan luar biasa bagi lidah. 🍲 Perjalanan ke Xinxiang kali ini menjadi lebih berkesan berkat kehadiran Bailie Yisu Shisu. Jika kamu juga bosan dengan keramaian kota dan ingin mencari tempat tenang untuk melepas penat, tempat ini pasti pilihan yang tepat. 💖LunaShadowborn_66Teluk Baoquan Youlong, matahari terbit di awal musim dingin mempesona dengan cahaya keemasan.
Di awal musim dingin, matahari terbit di Baoquan sungguh memukau, bak adegan udara sinematik. Matahari terbit di Baoquan tak hanya mewujudkan keindahan yang luas, tetapi juga membawa harapan yang lebih agung dan emosi yang unik dalam diri setiap orang. Saat cahaya keemasan memancar, seolah-olah alam semesta telah mengaktifkan sakelar di hati setiap orang, melepaskan gelombang energi yang tak menyisakan waktu untuk berpikir, hanya perasaan bahagia yang murni. Di momen istimewa ini, Teluk Youlong diselimuti jubah emas, menyambut semua pandangan, airnya yang mengalir semakin jernih. Inilah "China Quxia" yang ditampilkan di sampul majalah *China National Geographic*, dan dipuji oleh wisatawan sebagai "air mata biru Pegunungan Taihang." Fitur geografis yang unik dan matahari terbit yang memukau saling melengkapi, menciptakan panorama yang memukau. Di sini, pengunjung dapat merasakan kekaguman dan harapan yang dibawa oleh matahari terbit, merasakan sentuhan spiritual dan relaksasi. Selain itu, drone diizinkan di Baoquan, memungkinkan Anda mengabadikan momen menakjubkan "Sinar Matahari di Teluk Youlong" dengan kamera Anda. Datanglah ke Baoquan, abadikan keindahan unik ini, dan ciptakan kenangan tak terlupakan!Trip.PulseLiburan Keluarga ke Baoquan, Henan! Itinerary Sehari yang Direkomendasikan oleh National Geographic
Ikuti panduan National Geographic dan jelajahi keajaiban Gunung Taihang bersama anak-anak Anda! Ngarai-ngarai yang landai dan atraksi tebing yang mendebarkan di Area Pemandangan Baoquan cocok untuk anak-anak segala usia. Perjalanan sehari menawarkan keindahan alam dan wahana seru, menjadikan waktu keluarga Anda semakin berkesan! - 📍 Ikhtisar Area Pemandangan Terletak di Kabupaten Huixian, Xinxiang, Provinsi Henan, area ini terbagi menjadi dua area utama: "Tebing" dan "Grand Canyon." Keluarga dapat memilih atraksi yang disukai berdasarkan usia dan minat anak: - Tebing: Berpusat di sekitar keajaiban tebing, area ini menawarkan wahana seru seperti jalan kaca, roller coaster tebing, dan ayunan tebing, sempurna untuk orang dewasa yang gemar berpetualang. - Grand Canyon: Pada dasarnya merupakan negeri ajaib yang indah, dengan sungai dan air terjun, menawarkan pemandangan indah, ideal untuk fotografi dan pendakian yang mudah, cocok bahkan untuk anak-anak. - 🚶♀️ Rekomendasi Itinerary Keluarga Grand Canyon: Pintu Masuk Area Pemandangan → Mendaki ke "Taman Tulip" (nikmati bunga dan berfoto bersama anak-anak Anda) → "Lift Gua Berbentuk L" (rasakan sensasi naik lift unik, hemat energi) → (Lanjutkan dan kembali jika Anda ingin melihat air terjun) → Tiba di Cliff World dengan bus wisata. Cliff World: Kunjungi spot yang sama yang ditampilkan di majalah National Geographic → (Pilih bungee jumping/cliff swing sesuai keberanian anak Anda) → Hanging Corridor (berjalan kaki sekitar 2 jam; bagi yang staminanya kurang, bisa naik bus wisata) → Cliff Roller Coaster (pengalaman ramah keluarga) → Tulip Park → Luojia Temple Cableway (kapasitas 200 orang, sangat stabil) → Turun gunung dengan bus wisata - 🌟 Aktivitas Ramah Keluarga Cliff Swing, Cliff Roller Coaster, Bungee Jumping, Via Ferrata, dan Cliff Walk. Semua aktivitas perlu dipesan terlebih dahulu melalui akun WeChat resmi Baoquan. Bagi keluarga dengan anak-anak, disarankan untuk memilih aktivitas yang lebih aman seperti Cliff Roller Coaster dan Glass Walkway demi keamanan. - 💰 Detail Biaya Tiket Gabungan Area Pemandangan (termasuk Grand Canyon + Cliff World): - Tiket Dewasa: 220 RMB - Tiket Mahasiswa: 99 RMB - Lansia (60+), Guru, Jurnalis, Penyandang Disabilitas, Personel Militer, Pemadam Kebakaran, dan Polisi: Gratis masuk, tetapi dikenakan biaya antar-jemput area pemandangan sebesar 160 RMB. - Tiket masuk bulan April untuk wisatawan dari Jiangsu/Anhui/Hubei/Shaanxi: Gratis masuk, tetapi dikenakan biaya bus antar-jemput sebesar 160 yuan. Biaya bus antar-jemput: Grand Canyon 30 yuan, Cliffside 130 yuan - 🚌 Panduan Transportasi Keluarga Titik keberangkatan yang direkomendasikan: Zhengzhou/Xinxiang - Dari Zhengzhou: Anda dapat memesan tur satu hari dari Zhengzhou ke Baoquan. Tur ini nyaman dan langsung, sehingga tidak perlu khawatir dengan transportasi, sehingga cocok untuk keluarga dengan anak-anak. - Dari Xinxiang: Beli tiket bus dari Xinxiang ke Baoquan melalui program mini "Yuzhouxing". Fleksibel dan Anda dapat mengatur waktu Anda sendiri. - 📝 Tips Keluarga 1. Selain spot foto populer di lokasi foto "National Geographic", Cloud Cliff Walk juga merupakan objek wisata populer. Pastikan untuk memesan terlebih dahulu agar perjalanan Anda tidak sia-sia. 2. Rute pendakian di area wisata ini panjang. Pastikan anak-anak Anda mengenakan sepatu olahraga yang nyaman dan anti selip untuk memastikan keselamatan mereka. 3. Bawalah barang bawaan yang ringan. Bawalah pakaian pelindung matahari, topi, dan kacamata hitam. Matahari musim gugur sangat terik, jadi pastikan untuk melindungi diri Anda dari sinar matahari. 4. Selalu ikuti petunjuk keselamatan untuk aktivitas tebing. Orang tua dan anak-anak yang takut ketinggian harus berhati-hati saat memilih aktivitas di ketinggian. 5. Akhir pekan ramai, jadi kami sarankan untuk berkunjung pada hari kerja untuk pengalaman yang lebih baik dan antrean yang lebih pendek. 6. Jika Anda membawa anak-anak, bawalah camilan dan air minum. Terdapat juga penjual di dalam kawasan wisata dengan harga terjangkau. - [Panduan Akomodasi] Kami merekomendasikan Baoquan Secret Realm Hotel. Hotel ini memiliki suasana mewah bergaya alam bebas, berdekatan dengan kawasan wisata, dan menawarkan kamar-kamar nyaman yang ramah keluarga dengan fasilitas lengkap, sehingga memudahkan Anda untuk melanjutkan kunjungan keesokan harinya atau beristirahat sebelum kembali.NatureLover_Keajaiban Kristal Musim Dingin di Nan Taihang Xinxiang
Setiap tahun dari pertengahan Desember hingga Februari tahun berikutnya, Kawasan Wisata dan Resor Nan Taihang Xinxiang berubah menjadi dunia dongeng es dan salju, memulai petualangan kristal musim dingin yang eksklusif! Di sini, es stalaktit, embun beku, dan air terjun es membungkus seluruh pegunungan dengan lembut. Di bawah sinar matahari, gletser berkilauan seperti labirin kristal, ranting-ranting dipenuhi bunga es, setiap langkah terasa seperti menginjak serpihan bintang. Air terjun es setinggi ratusan meter bertingkat-tingkat, seperti seni patung es alami raksasa, dan saat mendekat, Anda bisa mendengar suara air mengalir samar di bawah lapisan es. Di hutan embun beku, ranting-ranting tertutup kristal es lembut yang bergoyang pelan tertiup angin, serpihan es jatuh dengan tenang, hingga Anda bisa mendengar detak jantung sendiri. Pengunjung dapat merasakan pengalaman romantis yang luar biasa di sini, foto tanpa perlu filter, dengan latar depan es menggantung, latar belakang gunung bersalju, cahaya samping yang memantul pada kabut es membentuk pelangi lembut, setiap jepretan seperti versi nyata dari "Frozen". Lokasinya berada di Kawasan Wisata dan Resor Nan Taihang Xinxiang, yaitu Baligou (Baligou·Tianjieshan·Jiulianshan), Wanshanshan, Guanshan, Qiugou·Qiwangzhai. Disarankan membawa sepatu anti selip, sarung tangan, pemanas tangan, dan hati yang tidak takut dingin serta penuh cinta romantis. Ayo datang ke Nan Taihang Xinxiang dan mulai perjalanan impian ini!Trip.PulsePetualangan Keluarga Baoquan! Panduan Tur Sehari Lengkap ke Pegunungan Taihang
Temukan pesona unik Pegunungan Taihang bersama anak-anak Anda! Area Pemandangan Baoquan memadukan pemandangan menakjubkan dengan aktivitas seru. Grand Canyon sempurna untuk balita berjalan-jalan dan menikmati pemandangan, sementara Cliff World memuaskan jiwa petualang orang dewasa. Perjalanan sehari ke sini penuh dengan aktivitas dan banyak keseruan untuk seluruh keluarga! - 📍 Ikhtisar Area Pemandangan Terletak di Kabupaten Huixian, Xinxiang, Provinsi Henan, area pemandangan ini terbagi menjadi dua area utama: "Cliff World" dan "Grand Canyon," yang melayani berbagai kelompok usia dan kebutuhan keluarga: - Cliff World: Menampilkan pemandangan tebing yang spektakuler dan aktivitas seru seperti jalan setapak kaca, roller coaster di sisi tebing, dan ayunan di sisi tebing, cocok untuk anak-anak dan orang tua yang suka berpetualang. - Grand Canyon: Ditandai dengan pemandangan yang indah, dengan aliran sungai yang gemericik, air terjun yang mengalir, vegetasi yang rimbun, dan udara segar, sempurna untuk balita mendaki dan berfoto. - 🚶♀️ Rekomendasi Itinerary Keluarga Grand Canyon: Pintu Masuk Area Pemandangan → Mendaki ke "Tulip Park" (Nikmati bunga dan tanaman berwarna-warni, berfoto bersama anak-anak Anda) → "Lift Gua Berbentuk L", tangga pertama di dunia (pengalaman lift gua yang unik, menghemat energi pendakian) → (Jika anak-anak memiliki energi yang cukup, mereka dapat melanjutkan melihat air terjun dan kemudian kembali) → Naik bus wisata ke Cliff World Cliff World: Kunjungi spot foto bertema "National Geographic" → (Pilih pengalaman berdasarkan tingkat kemampuan anak-anak) → Koridor Gantung (sekitar 2 jam berjalan kaki; bagi yang energinya terbatas dapat naik bus wisata langsung ke kereta gantung) → Roller Coaster Tebing (pengalaman ramah keluarga yang penuh kecepatan dan keseruan) → Tulip Park untuk beristirahat → Kereta Gantung Kuil Luojia (sangat stabil, dapat mengangkut 200 orang) (orang) → Naik bus wisata menuruni gunung - 🌟 Pengalaman Ramah Keluarga "Cliff Swing", "Cliff Roller Coaster", "Bungee Jumping", "Via Ferrata", "Cloud Cliff Walk"—semua aktivitas memerlukan pemesanan terlebih dahulu melalui akun WeChat resmi Baoquan. Bagi keluarga dengan anak-anak, disarankan untuk memprioritaskan aktivitas yang lebih aman dan seru seperti cliff roller coaster dan glass walker. - 💰 Detail Biaya Tiket Kombo Area Pemandangan (termasuk Grand Canyon + Cliff World): - Tiket Dewasa: 220 RMB - Tiket Mahasiswa: 99 RMB - Lansia (60+), Guru, Jurnalis, Penyandang Disabilitas, Personel Militer, Pemadam Kebakaran, Polisi: Masuk gratis, bayar 160 RMB untuk bus antar-jemput - Wisatawan dari provinsi Jiangsu, Anhui, Hubei, dan Shaanxi pada bulan April: Masuk gratis, bayar 160 RMB untuk bus antar-jemput Biaya Bus Antar-Jemput: Grand Canyon 30 RMB, Cliffside 130 RMB - 🚌 Panduan Transportasi Keluarga Titik Keberangkatan yang Direkomendasikan: Zhengzhou/Xinxiang - Keberangkatan dari Zhengzhou: Kami merekomendasikan untuk mengikuti tur satu hari "Zhengzhou-Baoquan", dengan transportasi bus lengkap, nyaman dan bebas repot, cocok untuk keluarga dengan anak-anak, tanpa perlu khawatir tentang masalah transportasi - Keberangkatan dari Xinxiang: Beli tiket bus dari Xinxiang ke Baoquan melalui program mini "Yuzhouxing", atur rencana perjalanan Anda sendiri, fleksibel dan nyaman. - 📝 Tips Keluarga 1. Destinasi foto populer "Cloud Cliff Walk" dan "National Geographic Magazine" memerlukan reservasi terlebih dahulu. Disarankan untuk melakukan reservasi satu hari sebelum keberangkatan agar tidak ketinggalan pada hari keberangkatan. 2. 1. Terdapat banyak rute pendakian di area wisata ini. Pastikan anak Anda mengenakan sepatu atletik yang nyaman dan anti selip untuk memastikan keamanan dan mencegah terpeleset. 2. Musim gugur adalah musim dengan sinar matahari yang terik. Bawalah pakaian pelindung matahari, topi, dan kacamata hitam untuk melindungi anak Anda dari sinar matahari. 3. Objek wisata tebing memiliki batasan usia dan tinggi badan tertentu. Keluarga dengan anak-anak harus memeriksa batasan ini terlebih dahulu dan mengikuti petunjuk keselamatan. Bagi yang takut ketinggian harus berhati-hati. 4. Akhir pekan sangat ramai. Disarankan untuk bepergian pada hari kerja untuk mengurangi waktu antre dan meningkatkan pengalaman. 5. Bawalah camilan, buah, dan air minum untuk anak Anda guna mengisi kembali energinya. Harga di toko-toko di area wisata ini cukup terjangkau. - [Panduan Akomodasi] Kami merekomendasikan Baoquan Secret Realm Hotel. Hotel ini menawarkan gaya resor mewah, dekat dengan area wisata, memiliki fasilitas ramah keluarga yang sangat baik, dan kamar-kamar dengan pemandangan Pegunungan Taihang yang luas, sehingga anak Anda dapat beristirahat dengan nyaman.RoosaRinneProyek Tebing Musim Dingin Baoquan Dimulai dengan Semangat
Desember ini, datanglah ke Baoquan untuk memulai petualangan musim dingin! Musim dingin di Baoquan, pegunungan dan air membeku menjadi puisi, tebing yang penuh semangat, adalah waktu terbaik untuk mengoleksi jiwa Baoquan. Quxia Tiongkok · Teluk Youlong, melepaskan warna-warni musim gugur, air jernih membeku menjadi biru es yang dalam, seperti safir besar yang tertanam di antara tebing merah, ikuti jejak "Geografi Nasional Tiongkok" untuk foto yang sangat bagus. Jalan Tebing Danxia, berjalan di sepanjang jalur tebing merah, udara segar, pandangan jernih, romantisme terbatas di bulan Desember, lihat cahaya merah keemasan membalut ngarai dengan selendang tipis. Proyek tebing di Baoquan adalah cara yang bagus untuk menghangatkan tubuh di musim dingin, ayunan tali besar di tebing berayun ke ngarai, roller coaster tebing melaju di sepanjang tebing, via ferrata dan bungee jumping membuat Anda merasakan pelukan tebing, berdiri di tempat tinggi memandang keindahan ngarai musim dingin yang khusyuk. Selain itu, Baoquan juga menawarkan tiket gratis dan diskon setengah harga. Anak-anak dengan tinggi 1,2 meter ke bawah gratis tiket jika didampingi wali; anak-anak dengan tinggi 1,2 - 1,4 meter, lansia berusia 60 tahun ke atas dengan dokumen yang sah bebas tiket; guru rakyat, mahasiswa penuh waktu dengan pendidikan sarjana ke bawah dapat menikmati tiket setengah harga. Segera datang ke Baoquan, isi kenangan musim dingin Anda!Trip.PulseUtopia kopi ini tersembunyi jauh di Pegunungan Taihang
Kedai kopi utopia yang tersembunyi jauh di Pegunungan Taihang ini memungkinkan saya untuk mencuri waktu luang setengah hari di tengah jadwal kerja 996 yang melelahkan. Tak perlu cuti kerja, tak perlu pemandu wisata—surga terpencil ini hanya berjarak 2 jam berkendara dari Zhengzhou: Yunduoli Homestay! 📍Yunduoli Homestay (Cabang Kawasan Pemandangan Baligou Taihang Selatan Xinxiang) Alamat: No. 83, Desa Songshuping, Kota Shangbali ▪️5 menit berjalan kaki ke Kawasan Pemandangan Baligou ▪️Di seberang pegunungan hijau yang megah, balkon dengan kursi rotannya menawarkan pemandangan pegunungan yang tak tertandingi ▪️Kamar ramah keluarga yang super terapeutik dengan perosotan dan kolam rendam di pintu masuk ☕Detail yang memukau: ✔️Kopi hand-drip-nya luar biasa! Biji kopi yang tersohor di dunia, menyeruput kopi di dekat jendela kaca panorama, dikelilingi pepohonan hijau yang rimbun—latar belakang yang sungguh memukau. ✔️Kamarnya setara hotel bintang lima, dengan jendela setinggi langit-langit yang menghadap pegunungan; bahkan piring buahnya pun dibuat dengan sangat apik. ✔️Pelayanan butlernya sangat ramah; AC sudah dinyalakan saat check-in. 📸Tips Fotografi: ▪️Ambil foto pegunungan yang memukau dari kursi rotan di balkon pada hari yang cerah. ▪️Perosotan di ruang keluarga sungguh menggemaskan (kenakan pakaian berwarna terang untuk foto yang lebih baik). ▪️Kolam di pintu masuk memantulkan hijaunya pegunungan; cahayanya paling indah saat senja. 💡Tips Berguna: ✅2 jam berkendara dari Zhengzhou; kunjungi "Yundoli Homestay". ✅Pesan kamar keluarga dengan perosotan terlebih dahulu—sangat populer di akhir pekan. ✅Bawalah jaket untuk musim gugur dan dingin; perbedaan suhu di pegunungan cukup signifikan, tetapi pemanasnya sangat baik. Saat Anda melangkah masuk, rasanya seperti dipeluk awan; semua kekhawatiran Anda tersapu oleh angin pegunungan. Sungguh homestay yang menenangkan dan terpencil di Pegunungan Taihang Selatan!EILEEN HORNPegunungan Taihang Selatan Xinxiang: Panduan Mendaki Mudah untuk "Retret Luar Ruangan"
Di Pegunungan Taihang Selatan Xinxiang, Anda dapat merasakan keseruan hiking "retret luar ruangan" yang unik, terutama cocok untuk "pemuda gunung" urban yang ingin menjelajah tetapi takut bekerja keras. Tersedia beragam pilihan hiking. Bagi pemula, terdapat Galeri Yunfeng Gunung Tianjie, tempat jalan setapak gantung yang mengelilingi gunung, menawarkan panorama 360° untuk kesempatan berfoto yang mudah. Jalan setapak kaca ini memberikan pengalaman yang sedikit mendebarkan, membuat seluruh pendakian terasa seperti berjalan di atas awan sekaligus memungkinkan Anda mengabadikan beberapa foto "Gunung Taihang yang menantang" yang mengesankan. Untuk pendakian yang lebih menantang, Anda dapat menantang Area Pemandangan Baligou, mengikuti suara air hingga Air Terjun Tianhe untuk "serangan oksigen" yang menyegarkan; atau melintasi Koridor Tebing Gunung Wanshan, merasakan sensasi pencapaian perpaduan unsur buatan manusia dan alam; dan Taman Guanshan Xiaoyao adalah hutan bak mimpi, dengan momen "wow" yang menakjubkan di One Line Sky. Jangan lewatkan tantangan mendaki gunung yang "ditingkatkan"! Di Puncak Laoye di Gunung Tianjie, naiklah kereta gantung hingga setengah jalan mendaki, lalu naiki anak tangga menuju puncak untuk menikmati panorama Pegunungan Taihang. Di Danfengou di Gunung Wanxian, naiklah bus wisata ke Desa Danfeng dan beristirahatlah di Air Terjun Heilongtan. Di Puncak Tianzhu di Guanshan, naiklah bus antar-jemput taman menuruni gunung, lalu naiklah; awan berkabut menciptakan kesempatan berfoto yang menakjubkan. Datanglah ke Pegunungan Taihang Selatan di Xinxiang, pilihlah rekan hiking Anda, dan temukan pengalaman unik ini bersama-sama, nikmati keseruan luar ruangan yang berbeda!Trip.PulsePetualangan Tebing Baoquan: Tantangan Musim Dingin Ekstrem Dimulai
Di bulan Desember, Baoquan memadukan kemegahan Pegunungan Taihang dengan kesegaran musim dingin dengan sempurna. Melangkah ke jalan setapak di sisi tebing Dan Cliff Sky Road, lembah-lembah yang dalam terbentang di bawah, sementara puncak-puncak yang berlapis menjulang di hadapan Anda. Pegunungan yang telah merontokkan daun-daun musim gugurnya tampak semakin luas dan megah di bawah hangatnya matahari musim dingin. Menyaksikan matahari terbit dan terbenam, setiap langkah merupakan dialog yang mendalam dengan alam. Ada juga pengalaman yang mendebarkan: ayunan tali raksasa menjuntai di tepi jurang, dengan jurang sedalam seratus meter di bawah dan pemandangan pegunungan yang luas di hadapan Anda; pendakian Via Ferrata mengubah Anda menjadi "penari batu", merasakan benturan batu dan kekuatan; lompat bungee tebing memungkinkan Anda melompat ke alam liar musim dingin, dengan nuansa tanpa bobot yang menggema di pegunungan – masing-masing merupakan penghormatan atas keberanian. Tebing Baoquan juga menyimpan romansa musim dingin. Dengan puncak-puncak gunung sebagai latar belakang, angin gunung yang bertiup di antara rambut Anda, setiap jepretan adalah mahakarya sinematik. Ikuti *Geografi Nasional Tiongkok* untuk mengabadikan momen-momen tak terlupakan di sepanjang jalan setapak tebing dan sepanjang jalan setapak – ini adalah "kenangan terbatas" musim dingin yang unik. Selain itu, anak-anak dengan tinggi badan 1,2 meter ke bawah dapat masuk taman secara gratis, dan anak-anak dengan tinggi badan antara 1,2 dan 1,4 meter, serta lansia berusia 60 tahun ke atas juga dapat menikmati tiket masuk gratis. Guru dan siswa dapat menikmati tiket masuk setengah harga. Datanglah ke Baoquan dan ikuti petualangan di tebing!Trip.PulsePanduan Menghindari Masalah Saat Liburan Keluarga di Baoquan
Siapa yang paham! Bagian paling melelahkan saat membawa anak jalan-jalan bukan berjalan kaki, tapi mencari tempat parkir + menggendong barang sambil buru-buru ke tempat wisata! Kali ini menemukan penginapan ajaib di seberang Baoquan, hanya 5 menit jalan kaki langsung ke pintu masuk, anak-anak bermain sampai tidak mau pulang~🚗✨ 🌊Wajib main di Baoquan: Rute ganda ramah anak dan menantang 👶Rute ramah anak (tingkat kesulitan 0! Bebas bermain air) - Kolam dangkal: Kedalaman hanya sampai pergelangan kaki, anak-anak bisa menangkap ikan dan udang sepuasnya - Bendungan sisik ikan: Ombak memukul bendungan berwarna-warni, foto seperti di tepi laut🌊 🎢Rute tantangan menantang (untuk yang berani) - Ayunan tebing: Ayunan dengan ayunan 180°, teriak sampai suara serak - Platform pemandangan awan keberuntungan: Platform kaca seluas 1739㎡, di bawah kaki adalah tebing setinggi 336 meter🌁 - Bungee jumping: Yang berani melompat adalah pahlawan! Harus reservasi dulu 🏡Bonus penginapan: Penginapan keluarga Qingyaxuan Kali ini menginap di Qingyaxuan·Luxury penginapan pemandangan pegunungan langsung luar biasa! 100 meter dari tempat parkir wisata, pemilik menyediakan antar-jemput gratis dengan mobil, waktu yang dihemat bisa dipakai main 2 atraksi lagi👌 Kamar dengan seluncuran untuk keluarga wajib dipilih! Tempat tidur susun + kombinasi seluncuran, anak langsung mulai bermain gila saat masuk kamar, tempat tidur atas dilengkapi pagar pengaman sangat perhatian. Kamar juga ada tenda anak dan elemen kartun, foto-fotonya sangat keren~ - ✅Rumah pintar: Kontrol lampu dan tirai dengan suara Xiaodu, membebaskan tangan - ✅Jendela lantai ke langit-langit: Pemandangan tanpa hambatan Baoquan benar-benar puncak liburan keluarga di Henan! Menginap di penginapan yang tepat langsung membuka cara bermain yang santai, keluarga bawa anak tinggal langsung datang saja!清雅軒民宿(河南寶泉旅遊區店)Diskon Musim Dingin Nan Taihang Xinxiang Hadir
Mulai 1 Desember hingga 31 Desember 2025, acara diskon musim dingin Nan Taihang Xinxiang dimulai! Di sini, sinar matahari hangat menyinari tebing batu merah yang curam, menciptakan bayangan unik yang bergantian terang dan gelap; air terjun di pegunungan berpadu dengan kicauan burung, menambah kehidupan pada keheningan musim dingin; puncak-puncak jauh berdiri tegak dan kuat di antara kabut, dengan kontur yang semakin jelas di bawah cahaya langit yang jernih. Duduk tenang di atas batu yang menghadap matahari, menyaksikan pergantian cahaya dan bayangan, mendengarkan bisikan angin, merasakan kelembutan penyembuhan musim dingin Taihang, dan menikmati udara segar dengan santai dan nyaman. Selama periode acara, banyak diskon tersedia, Baligou memberikan manfaat khusus bagi penduduk Xinxiang. Penduduk dengan KTP Xinxiang, penduduk yang tinggal lama dengan surat izin tinggal yang sah, dan mahasiswa dengan kartu pelajar dapat menikmati diskon istimewa 45 yuan/orang (termasuk transportasi besar di dalam kawasan wisata, harga asli 160 yuan/orang). Segera datang ke Nan Taihang Xinxiang dan rasakan keindahan musim dingin!Trip.Pulse11.22 Langsung|Xuyi, musim gugur dalam buku pelajaran.
Setiap kali datang ke Xuyi selalu terpesona oleh keindahannya, langit selalu sangat biru, selalu ada pemandangan yang berbeda, mengikuti jalan juga pergi ke Gunung Jiaoding untuk melihat matahari terbenam, Gunung Jiaoding jika datang di musim panas pasti sangat indah. 📍: Hutan Metasequoia (dilengkapi peta) 🅿️: Mobil bisa diparkir di pinggir jalan Daun-daunnya belum sepenuhnya merah, bisa menunggu satu minggu lagi untuk datang. Hutan metasequoia sebenarnya tidak terlalu besar, tapi sangat fotogenik, saat datang juga bertemu dengan drone🎬, jika berkeliling di Xuyi bisa mampir untuk bersantai.VentMarinMystic
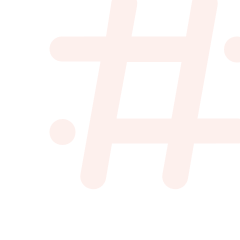
Topik Huixian Populer

2025 Recommended Pedoman in Huixian (Updated Desember)
429 post

2025 Recommended Atraksi wisata in Huixian (Updated Desember)
428 post

2025 Recommended Pedoman lengkap in Huixian (Updated Desember)
109 post

Destinasi yang terkait dengan Huixian

2025 Luoyang Travel Guide: Must-see attractions, popular food, hotels, transportation routes (updated in Desember)
1460 post

2025 Kaifeng Travel Guide: Must-see attractions, popular food, hotels, transportation routes (updated in Desember)
759 post

2025 Yuntai Mountain Travel Guide: Must-see attractions, popular food, hotels, transportation routes (updated in Desember)
13 post
- 1
- 2
- 3
- 4
- 13
Posting
Rekomendasi Lainnya
Popular Trip Moments
Tempat Check-in Baru di Baoquanyan Tianxia Telah Dibuka | Salju Pertama Musim Dingin di Gunung Wanxian | Panduan Lengkap Rekomendasi Bǎoquán | Guoliang Cliffside Highway: Sebuah perjalanan melalui sejarah sinematik 20 tahun "Raise Your Hands". | Pegunungan Taihang yang megah membentang sejauh delapan ratus mil, mencakup sejarah dua ribu tahun. | Musim Dingin di Guoliang | Saat salju menutupi Pegunungan Taihang, saya mendengar batu-batu bernapas! | Pendakian musim dingin di Pegunungan Taihang Selatan: Kerajaan es dan salju sungguhan, sangat indah. | Perjalanan Menjelajahi Keajaiban Pegunungan Taihang: Panduan Lengkap ke Gunung Wanshan di Henan | Rahasia Baliyigou! Menginap di Rumah Dewa | Teluk Baoquan Youlong, matahari terbit di awal musim dingin mempesona dengan cahaya keemasan. | Liburan Keluarga ke Baoquan, Henan! Itinerary Sehari yang Direkomendasikan oleh National Geographic | Keajaiban Kristal Musim Dingin di Nan Taihang Xinxiang | Petualangan Keluarga Baoquan! Panduan Tur Sehari Lengkap ke Pegunungan Taihang | Pemandu Wisata Satu Hari di Gunung Wanshan, Desa Guoliang, Jalan Raya Tebing | Proyek Tebing Musim Dingin Baoquan Dimulai dengan Semangat | Utopia kopi ini tersembunyi jauh di Pegunungan Taihang | Pegunungan Taihang Selatan Xinxiang: Panduan Mendaki Mudah untuk "Retret Luar Ruangan" | Petualangan Tebing Baoquan: Tantangan Musim Dingin Ekstrem Dimulai | Diskon Musim Dingin Nan Taihang Xinxiang Hadir | 11.22 Langsung|Xuyi, musim gugur dalam buku pelajaran. | Panduan Tempat Tersembunyi di Pegunungan Taihang | Xinxiang Baligou | Homestay Tersembunyi di Dekat Pegunungan dan Tepi Air | Perjalanan Sehari yang Menenangkan ke Baoquan bersama Anak-anak Anda: Itinerary yang Menenangkan dan Melelahkan | Hewan-hewan menggemaskan di Kebun Binatang Wulongshan menyambut musim gugur, mengundang Anda untuk berinteraksi dan berkumpul bersama! | Menjelajahi Keajaiban di Tebing Desa Guoliang | Perjalanan tersembunyi di Baoquan! | Kota kuno paling diremehkan di Shanxi! Tur 2 hari 1 malam yang mendalam di Jincheng, jelajahi permata tersembunyi Taihang! | Danau Baiquan di Kabupaten Huixian | Negeri Impian Jiangnan, Tempat Mata Air Muncul Kembali | Danau Kecil Barat di Huixian Baiquan benar-benar luar biasa! | Tur berkendara sendiri ke Pegunungan Taihang Selatan dari Zhengzhou di musim gugur! Nikmati pemandangan ngarai dan danau yang menakjubkan dalam satu hari.
Recommended Attractions at Popular Destinations
Atraksi Wisata Populer di Bangkok | Atraksi Wisata Populer di Manila | Atraksi Wisata Populer di Tokyo | Atraksi Wisata Populer di Taipei | Atraksi Wisata Populer di Hong Kong | Atraksi Wisata Populer di Seoul | Atraksi Wisata Populer di Kuala Lumpur | Atraksi Wisata Populer di Los Angeles | Atraksi Wisata Populer di Shanghai | Atraksi Wisata Populer di New York | Atraksi Wisata Populer di Shenzhen | Atraksi Wisata Populer di Osaka | Atraksi Wisata Populer di Singapura | Atraksi Wisata Populer di London | Atraksi Wisata Populer di Guangzhou | Atraksi Wisata Populer di San Francisco | Atraksi Wisata Populer di Beijing | Atraksi Wisata Populer di Makau | Atraksi Wisata Populer di Bali | Atraksi Wisata Populer di Jakarta | Atraksi Wisata Populer di Paris | Atraksi Wisata Populer di Kota Ho Chi Minh | Atraksi Wisata Populer di Istanbul | Atraksi Wisata Populer di Phuket | Atraksi Wisata Populer di Chicago | Atraksi Wisata Populer di Seattle | Atraksi Wisata Populer di Toronto | Atraksi Wisata Populer di Orlando | Atraksi Wisata Populer di Cebu | Atraksi Wisata Populer di Chiang Mai
Tentang kami
Metode pembayaran
Mitra kami
Hak cipta © 2025 Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd. Semua hak dilindungi undang-undang
Operator situs: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.
Operator situs: Trip.com Travel Singapore Pte. Ltd.